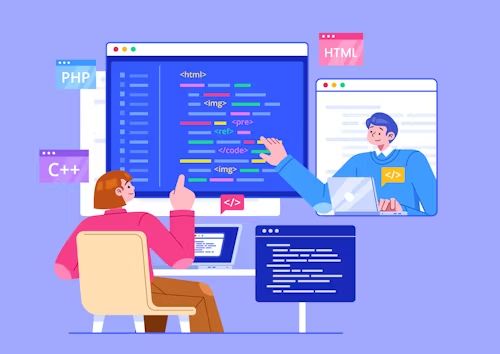Di balik semua hal teknis itu, ada keresahan lain yang pelan-pelan muncul teknologi berkembang begitu cepat, Ketika Teknologi Terlalu Cepat dan Manusia Tidak Sempat Mengikutinya sementara sumber daya manusianya kita semua tidak selalu punya ruang, tenaga, dan waktu untuk ikut tumbuh secepat itu.
Tulisan ini bukan ajakan untuk anti-teknologi.
Bukan juga keluhan “generasi Boomer” yang merasa ketinggalan zaman.
Ini lebih seperti catatan reflektif apa yang terjadi ketika teknologi berlari, manusia masih belajar jalan, dan ketimpangan baru mulai terasa di kantor, di rumah, di usaha kecil, bahkan di dalam kepala kita sendiri.
Daftar isi
Teknologi Berlari, Manusia Masih Belajar Jalan
Kalau kita mundur sedikit dan melihat dari jauh, pola ini kelihatan jelas:
- Dulu update software bisa setahun sekali.
- Sekarang, fitur baru bisa muncul tiap bulan, bahkan tiap minggu.
- Dulu belajar satu skill digital bisa dipakai bertahun-tahun.
- Sekarang, banyak orang merasa perlu “re-skill” terus-menerus.
Teknologi terus di-upgrade:
AI makin pintar, workflow makin otomatis, tools makin banyak.
Tapi manusia?
- Otaknya tetap sama, tidak mendapatkan update tahunan.
- Energinya terbatas.
- Waktunya terbatas.
- Kapasitas mentalnya juga terbatas.
Kita bisa kagum dengan semua kemajuan ini.
Tapi di saat yang sama, wajar kalau kita juga merasa kewalahan.
Bukan Soal Gaptek, Tapi Soal Ritme Kehidupan
Sering kali, orang yang ketinggalan teknologi diberi label “gaptek”, seolah-olah masalahnya hanya soal kemauan belajar.
Padahal, sering kali masalahnya jauh lebih dalam ritme hidup manusia memang tidak dibuat untuk berlari secepat roadmap produk teknologi.
Bayangkan:
- Seorang karyawan yang harus mengerjakan pekerjaan harian, sambil dipaksa mempelajari aplikasi baru setiap kuartal.
- Pemilik UMKM yang harus urus stok, produksi, karyawan, keuangan, tapi juga “katanya harus” mengerti iklan digital, konten, AI, dan otomasi.
- Guru yang bukan hanya mengajar, tapi juga harus menguasai platform belajar online, aplikasi ujian, sampai laporan digital.
Bukan mereka tidak mau belajar.
Tapi:
- Waktunya sudah terkuras untuk bertahan hidup.
- Energinya habis untuk urusan dasar: kerja, keluarga, kesehatan.
- Ruang mental untuk bereksperimen dengan teknologi baru itu nyaris tidak ada.
Ini bukan sekadar soal paham atau tidak paham teknologi.
Ini soal apakah ritme hidup manusia masih diberikan tempat di tengah percepatan ini.
Ketimpangan Baru, Mereka yang Tahu dan Mereka yang Tertinggal
Perkembangan teknologi yang terlalu cepat pelan-pelan membuka bentuk ketimpangan baru.
Bukan cuma ketimpangan ekonomi, tapi juga ketimpangan pengetahuan, akses, dan kepercayaan diri.
Beberapa ketimpangan yang mulai terasa:
- Ketimpangan akses pengetahuan
Mereka yang punya waktu, koneksi internet yang baik, dan lingkungan yang suportif bisa terus belajar hal baru.
Sementara yang lain hanya bisa melihat dari jauh. - Ketimpangan penghasilan
Orang yang bisa menguasai tools baru (AI, otomasi, data) sering kali naik kelas lebih cepat.
Sementara orang yang pekerjaannya mudah digantikan oleh mesin, mulai merasa posisinya tidak aman. - Ketimpangan psikologis
Ada yang percaya diri karena merasa “update”.
Ada juga yang makin cemas dan merasa “bodoh”, hanya karena tidak mampu mengejar semua perubahan yang ada. - Ketimpangan budaya kerja
Perusahaan yang cepat adaptasi kadang lupa bahwa manusia punya batas. Semua dikejar efisiensi, tapi tidak semua orang punya kemampuan atau kesiapan mental yang sama.
Pada titik ini, teknologi bukan lagi sekadar alat.
Ia mulai membentuk hierarki sosial baru siapa yang layak, siapa yang tertinggal.
SDM yang “Dipaksa” Pintar Seketika
Di banyak tempat kerja, narasi yang sering terdengar sekarang adalah:
“Kalau tidak mau belajar teknologi baru, nanti tertinggal.”
Sekilas, kalimat ini benar.
Tapi kalau kita lihat pelan-pelan, ada tekanan halus di dalamnya.
Contohnya:
- Karyawan yang sebenarnya sudah bekerja dengan baik, tiba-tiba dinilai “kurang adaptif” hanya karena lambat menguasai software baru.
- Orang yang sudah lama berkarya di satu bidang, mendadak merasa tidak berguna karena muncul AI yang bisa melakukan sebagian tugasnya.
- Tim operasional, admin, dan staff lapangan yang terbiasa kerja manual, tiba-tiba diminta mengerti dashboard, integrasi, dan automasi tanpa pendampingan yang cukup.
Yang sering terjadi:
- Training hanya formalitas.
- Ekspektasi naik, tapi dukungan tidak seimbang.
- Semua orang diminta “up to date”, tapi tidak semua diberi ruang belajar.
Padahal, kualitas SDM tidak bisa di-upgrade seperti update versi aplikasi.
Ketika “Belajar Terus” Justru Melelahkan
Di era ini, belajar tidak lagi sekadar kebutuhan.
Belajar hal baru menjadi tuntutan permanen.
Setiap hari seperti ada pesan tidak tertulis:
- “Harus tahu AI terbaru.”
- “Harus coba tools baru.”
- “Harus ikut tren baru.”
- “Harus makin produktif.”
Masalahnya, manusia tidak bisa terus menerus hidup di mode “belajar darurat”.
Akibatnya:
- Banyak orang merasa lelah secara mental, bukan karena bodoh, tapi karena kebanyakan informasi.
- Muncul rasa bersalah: “kok aku ketinggalan ya?”, padahal yang terjadi bukan kurang usaha, tapi terlalu banyak hal yang harus diikuti.
- Kualitas hidup pelan-pelan turun, karena teknologi yang seharusnya membantu, justru jadi sumber tekanan baru.
Belajar itu penting.
Tapi kalau ritmenya tidak manusiawi, dia berubah jadi beban.
Perasaan Tidak pernah Cukup
Ada dampak lain yang lebih sunyi adalah cara kita memandang diri sendiri.
Ketika mesin makin canggih, AI makin pintar, otomatisasi makin rapi, banyak orang tanpa sadar mulai membandingkan diri mereka dengan sistem yang:
- Tidak lelah.
- Tidak butuh istirahat.
- Tidak emosi.
- Tidak punya beban hidup lain.
Pelan-pelan, muncul perasaan:
- “Aku lambat.”
- “Aku tidak sepintar itu.”
- “Aku tidak relevan lagi.”
Padahal:
- Manusia memang tidak didesain untuk hidup seperti CPU.
- Kita punya perasaan, batas energi, dan kebutuhan akan jeda.
Teknologi mengubah banyak hal, termasuk standar yang kita pakai untuk menilai diri sendiri. Dan ini salah satu bentuk ketimpangan paling halus: ketika manusia merasa semakin kecil di tengah sistem yang semakin besar.
Apa yang Sebenarnya Kita Butuhkan dari Teknologi?
Mungkin pertanyaan yang perlu kita ulang lagi bukan:
“Teknologi apa lagi yang harus saya pelajari?”
Tapi lebih ke:
“Teknologi seperti apa yang benar-benar membantu hidup saya?”
Karena pada akhirnya, teknologi seharusnya:
- Mengurangi beban kerja yang repetitif.
- Membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting.
- Memperluas akses, bukan hanya memperlebar jurang.
- Membuat hidup lebih manusiawi, bukan lebih mekanis.
Beberapa hal yang bisa kita jadikan pegangan:
- Tidak semua tren harus diikuti.
Pilih yang relevan dengan hidup atau kerja kita, bukan sekadar ikut arus. - Belajar boleh pelan tapi konsisten.
Tidak perlu menguasai semua tools sekaligus. Satu demi satu, dengan ritme yang realistis. - Teknologi adalah alat, bukan identitas.
Nilai diri kita tidak diukur dari seberapa banyak software yang kita kuasai, tapi dari bagaimana kita hidup, bekerja, dan memperlakukan orang lain.
Menyusun Ulang Hubungan dengan Teknologi
Kalau kamu juga merasa lelah dengan kecepatan dunia digital, mungkin beberapa langkah kecil ini bisa membantu:
- Tentukan fokus belajar tahunan, bukan harian.
Misalnya: tahun ini fokus belajar otomasi workflow dasar, tahun depan baru eksplor AI lebih dalam jangan takut tertinggal. - Beri batas konsumsi informasi.
Tidak semua update produk, drama teknologi, atau hype AI perlu diikuti setiap hari ikuti fundamentanya saja. - Normalisasikan untuk tidak tahu semuanya.
Wajar kalau kita terlambat tahu satu dua tools. Itu bukan dosa digital. - Cari teman belajar, bukan sekadar sumber tekanan.
Komunitas, rekan kerja, atau lingkungan yang mau saling bantu jauh lebih berharga dibanding sekadar timeline penuh pamer produktivitas. - Ingat bahwa istirahat juga bagian dari adaptasi.
Otak butuh jeda untuk memproses hal baru. Memaksa diri terus belajar tanpa henti justru bikin kita tidak menyerap apa-apa.
Dengan cara ini, teknologi mungkin tetap akan terasa cepat, tapi kita punya sedikit kendali atas bagaimana kita meresponsnya.
Kesimpulan
Menemukan Ritme Manusia di Tengah Dunia Mesin
Teknologi akan terus berkembang.
AI akan terus membaik.
Otomasi akan terus meluas.
Kita bisa kagum, kita bisa memanfaatkannya, tapi kita juga berhak mengakui bahwa:
- Tidak semua orang punya titik start yang sama.
- Tidak semua orang punya sumber daya yang sama.
- Tidak semua orang punya energi mental yang sama.
Ketimpangan muncul ketika kecepatan teknologi tidak diimbangi ruang bagi manusia untuk belajar, beradaptasi, dan bernapas.
Di titik itu, tugas kita bukan menolak teknologi, tetapi:
- Menyusun ulang prioritas.
- Memilih dengan sadar teknologi mana yang mau diikuti.
- Mencari ritme yang lebih manusiawi untuk diri sendiri.
Karena pada akhirnya, hidup setiap orang unik, begitu juga cara mereka berdamai dengan dunia yang bergerak terlalu cepat.
Dan kalaupun kita tidak selalu bisa berlari, berjalan pelan dengan arah yang tepat sering kali lebih sehat daripada memaksa diri sprint tanpa tahu mau ke mana.